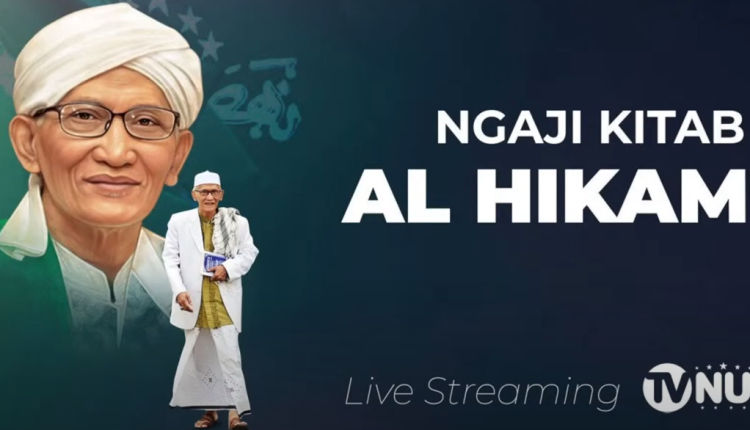قَالَ ذُو النُّونِ المِصْرِيُّ: إِذَا خَرَجَ المُرِيدُ عَنْ حَدِّ الأَدَبِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنْ حَيْثُ جَاءَ. وَقَالَ النُّورِيُّ: مَنْ لَمْ يَتَأَدَّبْ لِلْوَقْتِ فَوَقْتُهُ مَقْتٌ. وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: نَحْنُ إِلَى قَلِيلٍ مِنَ الأَدَبِ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَى كَثِيرٍ مِنَ العِلْمِ.
Dzunnûn al-Mishrî berkata: Apabila seorang murid keluar dari batas adab, maka ia akan kembali ke tempat asalnya. Al-Nûrî berkata: Barang siapa tidak beradab terhadap waktunya, maka waktunya akan berubah menjadi laknat baginya. Ibnu al-Mubârak berkata: Kami lebih membutuhkan sedikit adab dari pada banyak ilmu.
Kajian kali ini, kita disuguhkan sebuah teks dari kitab Syarah Hikam al-Athâ’iyah karya Ibnu Abbâd al-Nafarî. Teks tersebut memuat statemen beberapa tokoh penting dalam hirarki ilmu tasawuf, pertama Dzunnûn al-Mishri, salah seorang tokoh sufi terkenal yang bernama asli Tsaubân bin Ibrahim al-Mishri. Beliau dilahirkan di Kota Akhmim atau Ikhmim sebuah kota kuno yang berada di Tepi Timur Sungai Nil, pada tahun 179 H atau 795 M dan wafat pada tahun 246 H atau 856 M. Banyak sekali narasi yang dipaparkan para ulama mengenai penamaan Dzunnûn yang secara harfiah berarti “orang yang mempunyai huruf nûn”. Selanjutnya, huruf “nûn” oleh para ulama diartikan dengan “kemuliaan, keutamaan, dan kemurahan”. Sehingga, arti kata “Dzunnûn” adalah bapak kemuliaan, bapak keutamaan, dan bapak kemurahan. Apabila dikaitkan dalam konteks sejarah para nabi, Dzunnûn adalah sebuah gelar yang oleh al-Qur’an disematkan kepada Nabi Yunus waktu beliau dilempar dari kapal, lalu ditelan oleh ikan.
وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِبٗا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: “Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Anbiya, 21:87).
Menurut Dzunnûn al-Mishri, apabila seorang murid telah keluar dari batas-batas adab dan etika, maka ia telah kembali kepada asal sebelum ia menjadi seorang murid. Dalam pengertian umum, apabila seseorang sebelum menjadi murid atau kaum terpelajar tidak punya adab dan etika, maka hal itu wajar karena yang bersangkutan belum belajar mengenai etika yang baik. Tetapi, jika seseorang sudah menjadi murid dan kaum terpelajar, namun adab dan etika belum bisa melekat pada dirinya, maka berarti ia telah kembali kepada asalnya. Dalam epistemologi tasawuf, adab merupakan pagar bagi seorang murid (penempuh suluk spiritual) yang membatasi dirinya supaya perjalanan spiritualnya selalu berada pada jalur yang benar. Apabila sang murid mengabaikan adab dan etika yang memagarinya, lalu keluar dari batasan-batasan tersebut, ia akan kehilangan makna spiritual yang sedang dilaluinya. Dengan kata lain, kegagalan seorang penempuh jalan spiritual dalam menjaga adab dan etika, sama saja gagal dalam menempuh suluk spritual tersebut.
Kedua, adalah al-Nûri yang mempunyai nama lengkap Abû al-Hasan Ahmad bin Muhammad al-Nûri. Beliau dilharikan di Kota Baghdad sekitar tahun 225 H atau 840 M. Meskipun lahir di Kota Baghdad yang kala itu menjadi pusat peradaban Islam, namun asal usul beliau dari Khurasan, Persia. Menurut catatan al-Sulami dalam al-Tabaqâth al-Shûfiyah dan Abu Nu’âim al-Isfihâni dalam Hilyah al-Auliyâ’, al-Nûri adalah murid tokoh sufi yang masyhur, yakni Sirrî al-Saqati dan Junaid al-Baghdâdî. Sama seperti Rabi’ah al-Adawiyah, al-Nûri mengusung konsep al-Mahabbah atau cinta dalam suluk tasawufnya. Beliau wafat di Kota Baghdad sekitar tahun 295 H atau 908 M. Ia mendapat gelar al-Nûri yang berarti cahaya, karena kepekaan batin dan kedalaman ajaran tasawufnya, terutama lewat fanâ’ yang menjadi inti ajarannya.
Dalam pernyataannya: “Barang siapa tidak beradab terhadap waktunya, maka waktunya akan berubah menjadi laknat baginya”, al-Nûri hendak memberikan pengertian kepada kita, para pembaca bahwa mempergunakan waktu dengan bijaksana merupakan bagian dari suluk spiritual. Artinya, menurut al-Nûri waktu tidak hanya erat kaitannya dengan urusan duniawi, lebih dari itu, waktu adalah momentum untuk selalu merasakan kehadiran Allah s.w.t. setiap saat. Dalam konsep Fanâ’ yang diusung oleh al-Nûri, adab seorang murid terhadap waktu dalam menjalankan perjalanan spiritual, akan membatunya dalam mencapai peleburan ego ke-aku-an dalam dirinya. Sebab, jika ia melupakan ke-aku-annya setiap saat, maka yang ada hanyalah Allah. Dalam konsep tasawuf yang lain, ada istilah yang dikenal dengan Ibnu Al-Wakt atau putra waktu. Jika dipahami secara mendalam, Ibnu al-Wakt dalam pengertian di sini adalah ilustrasi mengenai seorang sufi yang selalu hidup tanpa diikat oleh waktu, baik pada masa lalu dan masa yang akan datang. Ia hidup di masa kini lantara selalu merasakan kehadiran Allah s.w.t. dalam dirinya.
Selanjutnya yang ketiga adalah Ibnu al-Mubârak, nama aslinya adalah Abdullâh bin al-Mubârak, seorang ulama besar dengan reputasi multidisiplin keilmuan yang melekat pada dirinya. Ibnu al-Mubârak hidup sekitar abad ke 2 hijriyah, lahir di kota Marw, Khurasan, Persia, tahun 118 H atau 736 M. Beliau termasuk salah seorang ulama yang menguasai hampir semua disiplin ilmu agama, baik tauhid, tafsir, hadits, fiqih, tasawuf, dan sebagainya. Dalam catatan al-Dzahabî dalam Siyar A’lâm al-Nubalâ’, setidaknya Ibnu al-Mubarak, pernah berguru kepada sekitar 4000 orang, di antaranya Imam Malik bin Anas, al-Auza’i, Sufyân al-Tsaurî, Abû Hanîfah, dan sebagainya. Sehingga wajar, jika reputasi keilmuwan yang beliau miliki tinggi, dan hampir semua ulama generasi setelahnya pernah berguru kepada beliau, di antaranya adalah Yahyâ bin Main, Nuaim bin Hammâd, Ishaq bin Rahâwaih, dan sebagainya. Ibnu al-Mubârak wafat di pada tahun 181 H atau 797 M, di Kota Hit, sebuah kota yang terletak di tepi sungai Eufrat.
Dalam pernyataannya, Ibnu al-Mubârak menegaskan bahwa ia lebih membutuhkan sedikit adab dari pada banyak ilmu. Tampaknya pernyataan tersebut kemudian menjadi kredo magis di kalangan para pelajar bahwa intisari dari ilmu adalah adab dan akhlak, sehingga dikatakan “al-Adab Fauqa al-Ilm”. Bila dipahami secara utuh, maka akan didapat sebuah pemahaman bahwa ilmu pada hakikatnya merupakan alat, sedangkan adab adalah penentu arah. Kita mungkin sering mendengar pepatah bahasa Inggris yang berbunyi “The Man Behind The Gun” , artinya manusia berada di belakang senjata. Jika dikaitkan dengan pejelasan Ibnu al-Mubârak di atas, maka ilmu itu ibarat senjata, sedangkan manusialah yang mengendalikannya. Senjata akan bermanfaat jika digunakan untuk hal-hal positif, sebaliknya ia akan menjadi malapetaka bila dipergunakan untuk hal-hal negatif. Kemampuan dalam mengontrol senjata itulah yang dalam bahasa Ibnu Mubârak disebut dengan adab atau etika. Tanpa adab dan etika, ilmu hanya akan menjadi sumber malapetaka bagi kehidupan manusia, dan dengan adab dan etika, ilmu justru mampu memajukan peradaban manusia, baik dari segi sains maupun teknologi.
Dalam dinamika kehidupan modern, seringkali ilmu dianggap sebagai representasi kecerdasan dan kemajuan manusia. Seorang ilmuwan mungkin dapat berbicara dengan cerdas, memecahkan masalah, dan bahkan mempengaruhi orang lain dengan teori pengetahuannya. Meskipun demikian, ilmu yang tinggi tidak secara otomatis menghasilkan kebajikan, karena tanpa adab, ilmu justru menjadi sumber keangkuhan dan kerusakan. Dalam realitas sosial, banyak orang berilmu tinggi yang kemudian menjadi angkuh, sombong, dan cenderung meremehkan orang lain, lantaran adab dan etika tidak menjadi dasar pijakannya. Sebaliknya, orang yang tidak banyak mengetahui teori pengetuan, tetapi memiliki adab akan lebih bermanfaat bagi lingkungannya. Ia mungkin tidak mampu menulis karya ilmiah yang kompleks atau berdebat dengan panjang lebar. Tetapi kehadirannya menyejukkan, tutur katanya menenangkan, dan sikapnya memancarkan kebijaksanaan.
Karena itu, maka kita mungkin sepakat bahwa pernyataan yang dikemukakan Ibnu al-Mubârak semakin kuat seiring dengan fakta yang kita temukan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, maka sejatinya manusia yang hidup dalam nilai-nilai seperti kesopanan, penghormatan, empati, dan kerendahan hati, jauh lebih penting dari sekedar mengumpulkan gagasan teori yang kaku. Apa gunanya teori ilmu komunikasi jika dalam tatanan praktis, ucapan yang dilontarkan sering kali membuat sakit hati orang lain? Lalu, apa artinya pengetahuan agama yang luas jika digunakan untuk merendahkan orang lain? Kemudian apa gunanya teori hukum jika hanya digunakan untuk menindas kaum lemah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mengindikasikan bahwa adab adalah kunci sebagai ejawantah dari ilmu nafi’. Wallâhu A’lam
(Pengajian Syarah Hikam Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar pertemuan ke-91 live di chanel youtub multimedia khmiftach).