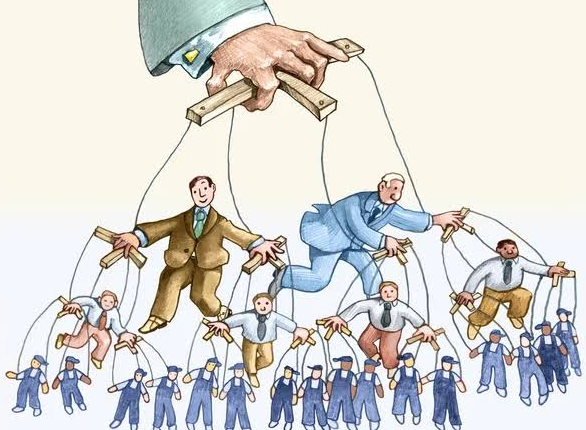Oleh: Dilhas Arsanamulia Madaaisyika (MA Qudsiyyah, Kudus, Jawa Tengah).
Hembusan angin malam menyelinap lewat jendela kamarku yang terbuka. Lembut, tapi dingin, seakan membawa pesan yang samar.
Di atas meja kayu sederhana, dua benda berhadap- hadapan: kitab kuning Ushul Fiqh dengan lembaran kertasnya yang menguning, dan laptop tipis dengan cahaya putih yang menyilaukan. Seakan keduanya sedang berdebat di hadapanku, sementara aku hanya menjadi penonton yang gamang.
Aku, Dilhas, santri di Madrasah Aliyah, hidup di antara dua kutub yang selalu terasa tegang: tradisi yang kukuh di satu sisi, modernitas yang mendesak di sisi lain. Kitab kuning itu bagaikan suara masa lalu yang tak pernah pudar, sedangkan layar laptop bagaikan seruan masa kini yang tak bisa diabaikan.
Aku menatap keduanya, lalu berpikir dengan cara yang selalu kuakrabi: logika.
Pertentangan itu bukan hanya antara benda mati di mejaku, tapi juga perang sunyi dalam dadaku. Artikel Liberal Islam karya Charles Kurzman yang kubaca di layar laptop memaparkan gagasan tentang demokrasi, hak perempuan, kebebasan berpikir. Sementara di lembaran kitab kuning, syarah para ulama bicara tentang kaidah, maqashid, dan kesalehan. Dua arus ini seakan hendak masuk sekaligus ke dalam pikiranku, tapi jalannya sempit. Apakah keduanya bisa bertemu tanpa saling meniadakan?
Aku teringat masa mula-mula menjadi santri di pesantren ini. Aku datang dengan kepala penuh cita-cita: menghafal kitab, memperdalam fiqih, lalu pulang menjadi penerang kampung halaman. Namun, hari-hari berjalan, aku justru menemukan bahwa pesantren bukan hanya ruang mengaji, melainkan juga arena berpikir. Di sinilah aku belajar bahwa pertanyaan bisa lebih berat daripada jawaban.
Madrasah Aliyah tempatku belajar adalah wajah unik dari pesantren: ia masih teguh dengan wirid, tahlil, hormat pada kiai, tapi sekaligus membuka ruang diskusi tentang demokrasi, sains, bahkan filsafat Barat. Dari luar, banyak orang menganggap itu kontradiksi. Tapi bagi kami yang hidup di dalamnya, kontradiksi justru adalah nafas sehari-hari.
Malam ini, ketika angin menelusup di sela buku-buku dan tirai, aku merasa hidupku sendiri adalah silogisme yang belum selesai.
Tanganku menyentuh kitab kuning. Aku membaca baris-baris kalimat Arab yang indah tapi berat, menjelaskan kaidah al-umur bi maqashidiha—segala perkara tergantung pada tujuannya. Kata-kata itu berkilau seperti kunci. Apakah mungkin tujuan syariat justru sejalan dengan tuntutan zaman?
Aku lalu menoleh ke laptop. Artikel Kurzman menekankan pentingnya demokrasi sebagai sarana melindungi kebebasan dan hak asasi. Jika kebebasan berpikir adalah hak dasar manusia, bukankah itu sejalan dengan maqashid al-syari’ah yang menjaga akal dan jiwa?
Pertanyaan demi pertanyaan muncul. Setiap kali aku mencoba menggabungkan keduanya, suara lain dalam diriku berkata: “Hati-hati, Dilhas. Jangan-jangan engkau tergelincir, menggadaikan iman demi modernitas.” Tapi kemudian, logika lain menyela: Jika yang aku pegang adalah maqashid, yaitu tujuan syariat, maka menerima modernitas bukanlah menggadaikan iman, melainkan cara baru menegakkan iman. Aku tersenyum pahit. Malam ini seakan otakku adalah majelis debat, kitab kuning duduk di sisi kanan, laptop di sisi kiri, dan aku sebagai moderator yang kebingungan. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan, seolah menertawakan kegelisahanku. Tapi aku tahu, kegelisahan inilah yang membuatku terus mencari. Jika aku berhenti gelisah, mungkin aku berhenti hidup sebagai pencari ilmu.
Madrasah ini sering disebut orang sebagai metamorfosis pesantren: tak sepenuhnya tradisional, tapi juga belum total modern. Di dalamnya, suasana khidmat bercampur dengan gelisah. Khidmat oleh doa-doa yang terus mengalun setiap malam, gelisah oleh diskusi santri- santri muda yang tak henti mempertanyakan. Kami membaca kitab turats dengan takzim, tapi juga membandingkannya dengan teori-teori sosiologi, ekonomi, bahkan filsafat kontemporer.
Di sinilah aku belajar arti paradoks: sesuatu bisa tampak berlawanan, tapi justru melahirkan sintesis.
Aku menutup laptop pelan, lalu menutup kitab kuning. Kedua dunia itu masih ada di hadapanku, tapi malam ini aku ingin menenangkan diri dengan doa. Dalam sujudku, aku memohon: “Ya Allah, tunjukkan jalan tengah, agar aku tidak buta oleh cahaya Barat, tapi juga tidak lumpuh oleh bayangan tradisi.” Dan aku tahu, esok pagi, pertentangan ini akan menemukan panggungnya di kelas—ketika Farid, temanku yang keras, menantang habis- habisan gagasan tentang demokrasi.
Keesokan paginya, ruang kelas itu dipenuhi cahaya matahari yang masuk dari jendela- jendela besar. Dindingnya berwarna putih kusam, papan tulis penuh coretan Arab gundul. Semua santri duduk bersila dengan kitab di pangkuan, suasana serius namun juga tegang. Hari ini, Kiai Rahmat memberikan kesempatan bagi para santri untuk menyampaikan pandangan mereka tentang hubungan agama dan modernitas.
“Baik,” suara Kiai tenang, “siapa yang ingin memulai?”
Farid segera mengangkat tangan. Tatapannya tajam, penuh keyakinan. Ia maju ke depan, berdiri dengan tegap. Suaranya keras, bagai palu yang menghantam meja sidang.
“Wahai saudara-saudaraku,” ia memulai, “Islam adalah agama sempurna. Allah sudah menurunkan syariat yang lengkap. Maka ketika manusia membuat aturan sendiri, seperti demokrasi, itu sama saja dengan menyaingi hukum Allah. Bukankah Allah berfirman dalam Qur’an, ‘Inil hukmu illa lillah’, tiada hukum kecuali milik Allah? Maka, segala bentuk demokrasi, pemilu, bahkan diskusi politik manusia adalah bentuk kekufuran terselubung. Kita tidak perlu meniru Barat. Modernitas adalah jebakan. Islam sudah cukup!”
Santri lain mulai berbisik-bisik. Ada yang mengangguk setuju, ada yang terlihat ragu.
Suasana Kelas Memanas
Farid menutup argumennya dengan suara meninggi: Ia kembali duduk dengan wajah penuh kemenangan.
Kiai Rahmat mengangguk pelan. “Baik, jelas argumennya. Ada yang ingin menanggapi?”
Dilhas menunduk sejenak. Dadanya berdebar. Kata-kata Farid menusuk, namun juga memanggil nalarnya untuk membalas. Perlahan ia mengangkat tangan.
Dengan langkah tenang ia maju ke depan. Suaranya tidak keras seperti Farid, namun dalam, penuh logika yang teratur.
“Saudaraku Farid,” ia membuka, “izinkan aku mengurai sedikit. Engkau berkata hukum hanya milik Allah. Benar, tidak ada yang membantah. Tetapi mari kita perhatikan. Apakah semua rincian kehidupan manusia tertulis eksplisit dalam kitab? Apakah setiap perkara baru, seperti listrik, internet, vaksin, atau bahkan sistem pemerintahan, sudah ada dalam Al-Qur’an secara literal?”
Kelas hening.
Dilhas melanjutkan dengan struktur mantiq yang menjadi andalan logika di lingkungan madrasahnya:
“Premis pertama: syariat diturunkan untuk menjaga lima hal pokok—agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. (maqashid asy-syari’ah). Premis kedua: demokrasi, meski buatan manusia, memberikan ruang musyawarah, kebebasan berpendapat, dan mencegah tirani. Premis ketiga: sesuatu yang mendukung maqashid tidak bisa otomatis dianggap kufur. Konklusinya: demokrasi bisa menjadi wasilah, alat, untuk menegakkan tujuan syariat, bukan lawan dari syariat.”
Beberapa santri mulai mengangguk-angguk.
Farid langsung menyela, wajahnya memerah. “Tapi itu logika buatanmu! Dalilnya mana? Allah melarang kita berhukum kepada selain Dia!”
Dilhas menghela napas. Ia tersenyum tipis.
“Baik, mari kita lihat sejarah. Umar bin Khattab pernah menangguhkan hukuman potong tangan pada masa paceklik. Apakah Umar melawan hukum Allah? Tidak. Beliau justru memahami illat, sebab dari hukum itu, yakni menjaga keadilan. Umar membuat ijtihad demi maqashid. Begitu pula dengan demokrasi. Ia bukan tandingan wahyu, melainkan ijtihad sosial agar keadilan tidak mati. Jika demokrasi membawa maslahat, apakah kita harus menolaknya hanya karena lahir dari Barat?”
Kelas semakin gaduh. Ada yang bertepuk tangan pelan, ada yang berbisik “Masuk akal juga.” Dilhas menambahkan dengan gaya silogisme:
“Premis pertama: sesuatu disebut kufur bila menolak wahyu secara mutlak.
Premis kedua: demokrasi tidak menolak wahyu, hanya mengatur teknis musyawarah.
Konklusinya: menuduh demokrasi kufur adalah qiyas yang keliru, karena illat-nya tidak sama.”
Farid terdiam, wajahnya merah padam. Ia mencoba membuka mulut, namun kata-katanya tersangkut di tenggorokan.
Kiai Rahmat tersenyum tipis.
“Cukup. Diskusi ini sudah menunjukkan dua jalan berpikir: yang tekstual, dan yang maqashid. Keduanya harus dihormati. Tapi ingat, kebenaran bukanlah milik suara keras, melainkan milik hujjah yang kokoh.”
Suasana kelas kembali tenang, meski bara kecil masih tersisa di wajah Farid. Sementara itu, Dilhas duduk kembali dengan hati yang masih bergetar. Ia sadar, pertarungan logika baru saja dimulai.
Malam itu, setelah perdebatan panjang di kelas, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Farid masih bergema di telingaku, juga jawabanku sendiri yang meski logis, tetap menyisakan ruang keraguan. Aku tahu, jika dibiarkan, keraguan itu akan membesar. Maka aku memberanikan diri mendatangi ruang belajar Kiai Rahmat.
Ruang itu sederhana, tapi penuh dengan buku. Rak-rak kayu menjulang sampai langit-langit, dipenuhi kitab turats berbahasa Arab, tafsir, hadits, hingga buku-buku modern berbahasa Inggris dan Indonesia. Bau kertas tua bercampur dengan aroma kopi yang menenangkan.
Kiai Rahmat duduk di kursinya, sorot matanya teduh, seakan bisa menembus isi dadaku. “Dilhas, duduklah,” ujarnya pelan, namun penuh wibawa.
Aku duduk bersila di hadapannya, menunduk hormat. “Kiai, hari ini aku merasa seperti berdiri di tebing yang curam. Satu langkah salah bisa menjatuhkanku. Di kelas, aku berdebat dengan Farid soal demokrasi. Aku mencoba menjawab dengan maqashid al-syari’ah. Tapi di dalam hati, aku tetap bimbang. Apakah aku sedang mencari kebenaran, atau sedang membela diriku sendiri?”
Kiai Rahmat tersenyum samar. “Nak, pertanyaanmu itu justru tanda bahwa engkau sedang berada di jalan yang benar. Yang berbahaya bukanlah orang yang ragu, melainkan orang yang merasa tidak mungkin salah.”
Aku menatap beliau, menunggu penjelasan.
Kiai mengambil sebatang pena, lalu mengangkatnya. “Lihat pena ini. Jika aku katakan pena ini lurus, itu benar. Tapi jika aku taruh di dalam segelas air, engkau akan melihatnya bengkok. Apakah ia benar-benar bengkok?”
Aku menggeleng. “Tidak, Kiai. Itu hanya bias cahaya.”
“Benar,” ujar beliau. “Begitulah ilmu. Premis pertama: Ilmu adalah cahaya. Premis kedua: Cahaya bisa terpantul berbeda sesuai medium. Konklusinya: Tradisi dan modernitas bukanlah cahaya yang berbeda, tapi medium yang berbeda. Jika engkau hanya melihat dari satu medium, engkau akan mengira ada pertentangan, padahal keduanya memantulkan cahaya yang sama.”
Aku terdiam, mencerna perumpamaan itu.
Kiai melanjutkan. “Jangan puas hanya dengan fil qaul—sekadar mengutip pendapat ulama. Kau harus naik ke level fil manhaj—memahami metodologi mereka. Jika engkau hanya berhenti di qaul, engkau akan terjebak dalam perang kutipan: ulama A berkata begini, ulama B berkata begitu. Tapi jika engkau memahami manhaj, engkau akan bisa membangun jembatan antara qaul lama dan persoalan baru.”
Aku mengangguk perlahan. “Tapi Kiai, bukankah itu berbahaya? Bagaimana jika aku keliru memahami?”
“Justru itulah gunanya tradisi,” jawab beliau. “Tradisi adalah jangkar, modernitas adalah layar. Kapal tidak akan sampai tujuan tanpa layar, tapi kapal juga akan hanyut tanpa jangkar. Tugasmu sebagai santri adalah menjaga agar keduanya seimbang. Jangan tenggelam dalam romantisme masa lalu, tapi juga jangan hanyut dalam arus zaman.”
Kiai kemudian menunduk, tangannya menepuk kitab al-Muwafaqat di meja. “Imam Syathibi menulis tentang maqashid bukan untuk zaman kita saja, tapi untuk semua zaman. Premis pertama: Syariat itu diturunkan untuk membawa maslahah. Premis kedua: Bentuk maslahah bisa berubah sesuai ruang dan waktu. Konklusi: Maka cara menegakkan syariat pun bisa berbeda di setiap zaman, tapi tujuannya tetap sama.”
Aku merasa dadaku sedikit lapang. Namun kegelisahan masih menyisakan satu pertanyaan. “Kiai, kalau begitu… apa benar aku tidak sedang ‘Barat-isasi’? Banyak orang menuduh demokrasi, kebebasan berpikir, dan hak perempuan itu impor dari Barat.”
Kiai tertawa kecil, lembut tapi penuh makna. “Nak, jangan gampang tertipu label. Premis pertama: Semua ilmu berasal dari Allah. Premis kedua: Barat atau Timur hanyalah arah mata angin. Konklusi: Maka setiap hikmah, dari mana pun datangnya, tetap milik Allah. Apakah engkau menolak kompas hanya karena ia ditemukan orang Cina? Atau menolak aljabar hanya karena ia dikembangkan orang Persia?”
Aku terdiam. Logikanya sederhana, tapi menghantam kuat.
“Ketahuilah, Dilhas,” lanjut Kiai, “liberal yang sejati bukan berarti bebas tanpa batas. Liberal sejati adalah bebas dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu. Itulah yang dilakukan para ulama kita sejak dulu. Mereka tidak takut meminjam logika Yunani untuk memperkuat kalam, atau filsafat Persia untuk memperindah tafsir. Selama intinya adalah menjaga maqashid, itu bukan pengkhianatan, tapi justru kelanjutan tradisi.”
Aku merasakan sesuatu bergetar di dalam hati. Seakan beban panjang itu perlahan luruh.
Kiai menatapku tajam, tapi penuh kasih. “Jangan terjebak pada dikotomi hitam-putih. Dunia ini penuh gradasi. Tugasmu sebagai santri bukan menolak gradasi itu, melainkan menemukan keseimbangan di dalamnya. Seperti air: ia bisa menjadi lembut mengalir, tapi juga bisa memecah batu. Kelenturan itu bukan kelemahan, tapi kekuatan.”
Aku mengangguk, kali ini dengan mantap. “Terima kasih, Kiai. Aku merasa mendapat arah baru. Mungkin aku masih ragu, tapi setidaknya aku tahu bahwa keraguanku ini sedang diarahkan pada ilmu, bukan pada kebingungan kosong.”
Kiai tersenyum. “Itulah jalan seorang penuntut ilmu. Jangan pernah berhenti bertanya, tapi jangan pula berhenti bersujud.”
Aku berpamitan, membawa pulang cahaya yang berbeda malam itu. Bukan cahaya laptop atau kitab kuning semata, tapi cahaya pemahaman yang mulai membaur.
Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Ruang kelas dipenuhi santri dan beberapa kiai. Mata mereka menatapku dengan campuran rasa penasaran, skeptisisme, dan harapan. Farid duduk di barisan depan, tatapannya masih tajam, tapi ada kerling penasaran yang tak bisa ia sembunyikan.
Aku menarik napas panjang, lalu membuka esai yang sudah kubuat. Judulnya sederhana, tapi sarat maksud: “Maqashid al-Syari’ah dan Modernitas: Jalan Tengah Santri Masa Kini”.
Aku memulai dengan pertanyaan retoris, gaya mantiq yang selalu kuandalkan:
“Apakah benar kebenaran selalu hitam dan putih? Apakah setiap inovasi manusia harus dianggap ancaman, ataukah setiap tradisi hanya sah bila tidak menyerap pelajaran zaman?”
Hening menyelimuti ruangan. Semua mata menatapku, menunggu jawaban logis. Aku melanjutkan dengan premis:
“Premis pertama: Syariat diturunkan untuk menjaga lima maqashid—agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Premis kedua: Modernitas menghadirkan alat dan metode baru untuk melindungi maqashid tersebut. Premis ketiga: Alat dan metode baru tidak meniadakan prinsip. Konklusi: Maka menerima modernitas untuk melindungi maqashid bukanlah pengkhianatan, melainkan kelanjutan logis dari tradisi Islam.”
Aku mengangkat kitab kuning di tangan kiri dan laptop di tangan kanan.
“Lihatlah, dua benda ini. Kitab kuning adalah akar, laptop adalah cabang. Tanpa akar, cabang tidak akan berdiri. Tanpa cabang, akar tidak menua dan berbuah. Keduanya saling melengkapi. Tidak ada kontradiksi, hanya harmoni yang menunggu pemahaman kita.”
Aku menambahkan qiyas:
“Premis pertama: Nabi Yusuf menggunakan sistem Mesir untuk menyelamatkan rakyat dari kelaparan. Premis kedua: Umar bin Khattab menyesuaikan hukum potong tangan dengan kondisi paceklik. Konklusi: Mengadaptasi sistem manusia demi maslahat bukan pengingkaran, tapi aplikasi maqashid dalam konteks zaman.”
Beberapa santri mengangguk. Aku melihat Farid menunduk, matanya menatap lantai, seolah sedang menimbang logika demi logika yang kuurai.
Aku melanjutkan, mengaitkan hak asasi:
“Premis pertama: Islam menekankan keadilan bagi semua manusia. Premis kedua: Demokrasi memberikan ruang bagi perempuan, minoritas, dan kaum tertindas untuk disuarakan. Konklusi: Maka mendukung hak-hak mereka adalah implementasi keadilan, bukan pengkhianatan terhadap syariat.”
Aku berhenti sejenak, menatap seluruh ruangan. Suasana begitu tegang, tapi aku merasakan aliran logika mulai merasuk.
“Saudaraku, kita sering terjebak pada dikotomi: fundamentalis versus liberal, tradisional versus modern. Padahal khazanah Islam sendiri kaya dengan pemikiran humanis. Premis pertama: Syariat diturunkan untuk maslahat. Premis kedua: Maslahat bisa diwujudkan melalui berbagai cara sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip. Konklusi: Maka liberalisme dalam Islam sejati bukanlah Barat atau anti-tradisi, tetapi pengakuan atas hikmah syariat yang dinamis.”
Aku melihat Kiai Rahmat tersenyum tipis, matanya teduh tapi penuh makna. Santri lain mulai berbisik, beberapa mengangguk. Farid masih diam, namun dadanya tampak lebih lega.
Setelah presentasi, Farid menghampiriku. Suaranya pelan, hampir tak terdengar.
“Dilhas… aku tidak setuju dengan semua yang kau katakan. Tapi aku mulai mengerti dari mana kau memandangnya. Aku ingin membaca lebih banyak tentang maqashid itu.”
Aku tersenyum, menepuk pundaknya. “Itulah yang kuharapkan. Bukan kemenangan mutlak, tapi pintu dialog yang terbuka.”
Malam itu, ketika lampu kamar menyala redup, aku duduk menatap dua sahabat lama: kitab kuning dan laptop. Kedua dunia itu kini tidak lagi saling menantang, melainkan berbicara satu sama lain, seperti dua aliran sungai yang akhirnya bersatu membentuk muara yang tenang.
Aku menarik napas panjang, lalu menuliskan refleksi di jurnalku:
“Kedalaman ilmu agama adalah cahaya yang tak tergoyahkan. Keterbukaan pada modernitas adalah medium yang memungkinkan cahaya itu bersinar lebih luas. Santri yang bijak harus mampu menyeimbangkan keduanya, agar cahaya tidak padam, dan arus zaman tidak menenggelamkan kebenaran.”
Aku merenungkan perjalanan hari ini. Di kelas, debat dengan Farid telah membuka jalanku untuk memahami bahwa konflik antara tradisi dan modernitas bukanlah perang, tapi dialog. Premis hitam-putih selalu menyesatkan: kebenaran tidak pernah sederhana. Seperti yang dikatakan Kiai Rahmat, air yang lentur bisa melewati batu keras, tetapi tetap mempertahankan hakikatnya.
Aku menulis lebih lanjut:
“Premis pertama: ilmu agama tanpa pemahaman kontekstual akan menjadi kaku dan tertutup. Premis kedua: buku tanpa pemahaman adalah kertas kosong. Konklusi: membaca dunia modern bukanlah pengkhianatan terhadap syariat, tetapi bagian dari ijtihad kontemporer untuk menegakkan maqashid.”
Di halaman lain jurnalku, aku menuliskan dialog batin yang terus berulang: “Apakah aku terlalu mengikuti arus zaman?”
“Tidak. Tujuan syariat adalah maslahat. Alat demi maslahat bisa berbeda setiap zaman. Maka, menggunakan alat zaman bukan pengkhianatan.”
Aku menutup jurnal. Suasana hatiku mulai tenang. Malam ini, aku menyadari bahwa perjalanan menyeimbangkan tradisi dan modernitas adalah perjalanan seumur hidup. Tiap debat, tiap perenungan, tiap bacaan baru, adalah langkah kecil menuju pemahaman yang lebih dalam.
Kedalaman kitab kuning memberiku jangkar, sedangkan modernitas memberiku layar untuk menavigasi dunia. Tanpa jangkar, aku akan hanyut; tanpa layar, aku akan buta menghadapi zaman. Seperti analogi air yang lentur, aku belajar: kelembutan dalam berpikir tidak bertentangan dengan kekuatan logika.
Aku menutup laptop, menyentuh kitab kuning, dan tersenyum. Premis terakhir dalam hatiku:
“Premis pertama: Pesantren adalah laboratorium pemikiran yang dinamis. Premis kedua: Keterbukaan pada ilmu dan dialog adalah jalan untuk menemukan kebenaran.Konklusi: Maka menjadi santri bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan mengalir di antara dua aliran, menyerap hikmah dari keduanya, dan menegakkan maqashid di setiap langkah.”
Aku merasa lega. Tidak ada kemenangan mutlak, hanya pemahaman yang semakin mendalam. Farid mungkin masih mempertahankan pandangannya, namun aku yakin dialog itu membuka jalan. Jalan yang sama yang suatu saat akan ditempuh oleh santri lain, dan bahkan aku sendiri, untuk menjembatani tradisi dan modernitas.
Malam itu, angin berhembus lembut. Aku menatap langit gelap yang bertabur bintang. Aku seperti air yang mengalir di antara batu-batu keras modernitas dan akar-akarnya tradisi. Lentur, tapi tetap setia pada hakikatnya. Begitulah aku belajar bahwa kebenaran tidak pernah hitam atau putih, dan pesantren bukan hanya tempat mengaji, tapi laboratorium untuk menumbuhkan pemikiran yang bebas, bermartabat, dan penuh belas kasih.