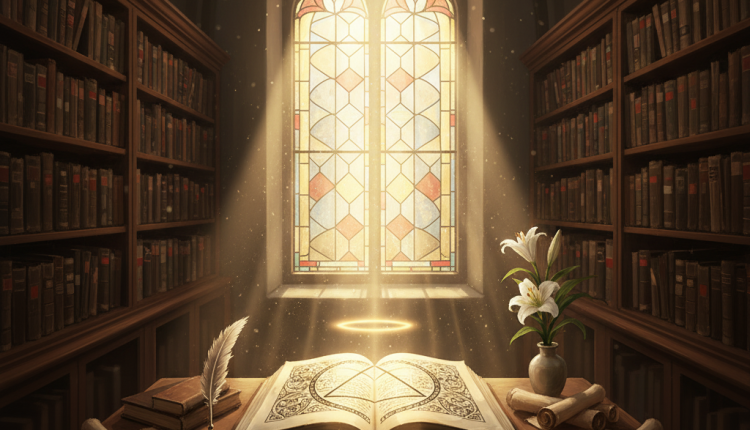Rasionalitas dibalik Gagasan Mengusung Eko Teologi dan Pelestarian Lingkungan sebagai Pelayan Keagamaan

Oleh: Prof. Dr. Zubaedi M. Ag M.Pd.
(Wakil Rektor 2 UIN Fatmawati Sukarno – Wakil Ketua PWNU Bengkulu).
Menteri Agama Nasaruddin Umar, meminta ekoteologi dan pelestarian alam masuk dalam kurikulum pendidikan agama dan keagamaan. Kementerian Agama RI mengusung pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari pelayanan keagamaan.
Ini ditunjukkan secara tegas dalam KMA Asta Protas Nomor 244 tahun 2025, yang menjadikan ekoteologi sebagai salah satu dari delapan prioritas transformasi layanan keagamaan. Dalam KMA tersebut, ditegaskan bahwa pelestarian lingkungan adalah panggilan iman, bukan sekadar anjuran moral.
Ekoteologi menurut Prof. Nasaruddin Umar adalah pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai agama, khususnya Islam, dengan isu-isu lingkungan. Ia menekankan pentingnya memperbaiki hubungan manusia dengan alam, karena kerusakan lingkungan adalah akibat dari ketidakseimbangan hubungan tersebut. Prof. Nasaruddin juga menyoroti pentingnya memperbaiki teologi masyarakat, yaitu cara pandang dan keyakinan yang mendasari perilaku manusia terhadap alam, agar tercipta kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Dengan kata lain, ekoteologi menurut Prof. Nasaruddin Umar adalah upaya untuk menyelaraskan hubungan manusia dengan alam melalui pemahaman agama yang lebih mendalam dan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
Terkait Eco-Theology, Menag menjelaskan bahwa itu menjadi landasan spiritualitas dalam upaya pelestarian lingkungan. Konsep “Eco-Theology” mengajarkan bahwa menjaga bumi bukan sekadar upaya ilmiah atau kebijakan negara, tetapi juga merupakan bagian dari spiritualitas dan ibadah kita kepada Tuhan.
“Gerakan lingkungan berbasis keagamaan telah berkembang di banyak tempat. Di Indonesia, kita telah melihat inisiatif masjid ramah lingkungan (eco-friendly mosque), pesantren hijau (green pesantren), gereja berkelanjutan, dan lainnya yang memanfaatkan energi terbarukan dan praktik ramah lingkungan. Ini adalah contoh-contoh baik yang harus terus kita kembangkan sebagai wujud nyata dari eco-theology dalam kehidupan umat beragama.
Pengarustamaan Isu Eko Teologi
Pengarustamaan isu eko-teologi ini rasanya sangat signifikan di tengah-tengah realitas semakin merosotnya lingkungan hidup kita. Jika kesadaran umat manusia dalam melestarikan lingkungan semakin menipis maka kerusakan lingkungan yang lebih parah tinggal menunggu waktu. Saat itu, tanda-tanda itu semakin nyata: udara, tanah dan air tercemar, tanah tandus dan gersang, berkurangnya vegetasi, deforestasi, kebakaran hutan, dan kerusakan ekosistem laut (akibat aktivitas manusia, punahnya flora dan fauna, serta meningkatnya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor dan lain-lain.
Pada hal agama Islam sudah memperingatkan umat manusia untuk tidak berbuat kerusakan terhadap alam. Setidak-tidaknya ada 9 ayat yang menyerukan kita untuk mencegah prilaku merusak alam, yaitu: Q.S Ar-Rum ayat 41; Q.S al-Baqarah ayat 11, 12, 30, dan 60; Q.S al-A’raf ayat 56, 74; Q.S al-Qasas ayat 77; dan Q.S Yunus ayat 41.
Dalam Q.S Ar-Rum ayat 41, Allah:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ, yang artinya: “telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar Rum: 41)
Atas dasar ini komitmen Kemenag untuk mengangkat isu ini menjadi prioritas kebijakan perlu disambut secara luas.
Sejatinya, roh atau spirit ajaran Islam adalah menekankan komitmen untuk ramah terhadap lingkungan. Dalam Islam, penggunaan sumber daya alam harus didasarkan pada aspek manfaat dan maslahat. Ajaran Islam jelas-jelas mengingatkan pada manusia untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang disediakan di alam disertai upaya melestarikan lingkungan hidup. Sebaliknya merupakan tindakan mubadzir dan mencelakan jika manusia tidak memanfaatkan sumber daya alam. Namun diingatkan Kiai Sahal, penggunaan sumber daya alam harus memenuhi ukuran-ukuran kemanfaatan dan kemaslahatan. Pemanfaatan sumber daya alam harus diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, diarahkan pada kepentingan hidup, kepentingan bersama, kepentingan agama dan lain-lain.
Mengutip pendapat Kiai Sahal Mahfudh, Islam menaruh perhatian tinggi terhadap pentingnya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Menurutnya, pembangunan harus memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini mengingat upaya pelestarian lingkungan menjadi kunci bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan akherat. Upaya pelestarian lingkungan diakui Kiai Sahal menyangkut upaya-upaya perlindungan terhadap berbagai kekayaan alam mulai dari tumbuh-tumbuhan, air, hewan dan unsur-unsur alam lainnya. Secara tegas, Kiai Sahal mengatakan:
“ Stabilitas hidup memerlukan keseimbangan dan kelestarian di segala bidang baik yang bersifat kebendaan maupun yang berkaitan dengan jiwa, akal, emosi, nafsu dan perasaan manusia. Islam sebagaimana pesan beberapa ayat al-Qur’an dan Hadis menekankan pola tawassuth dan i’tidal (keseimbangan)”.
Bahkan menurut al- Qur’an, umat Islam wajib menjaga keselamatan lingkungan hidup. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an Surat al- A’raf ayat 85:
ولا تفسد وا قي الا رض بعد اصلا حها ذ لكم خير لكم ان كنتم مؤ منين
Janganlah kamu sekalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.
Ayat di atas memberi pesan kepada manusia untuk menghindari eksploitasi kepada alam secara berlebihan dan merusaknya. Larangan ini lahir karena kerusakan alam akan berdampak pada kemiskinan dan sebaliknya pelestarian alam dan lingkungan akan berdampak positif bagi penciptaan kesejahteraan hidup manusia.
Mengingat sumber daya alam seperti hutan, air, udara dan sejenisnya berperan vital dalam menyangga kehidupan manusia, flora dan fauna maka Islam mengajarkan untuk secara bersama mempertahankan kelestariannya. Islam, ungkap Kiai Sahal, mengajarkan gerakan menjaga kelestarian alam di antaranya dengan menanam pepohonan. Berkaitan dengan hal ini, Nabi pernah bersabda:
اذا قامت الساعة وبين احدكم فسيلة فاستطاع ان يقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك اجر
Bila kiamat telah tiba dan ternyata di tangan kalian ada bibit tanaman yang mungkin ditanam maka tanamlah karena kalian dengan demikian mendapat pahala (HR Ahmad).
Upaya-upaya menjaga keselamatan lingkungan hendaknya menjadi kesadaran bersama. Semua elemen masyarakat harus bersinergis untuk merealisasikan gerakan ini. Di antara elemen sosial yang bisa mengambil peranan penting dalam upaya pelestarian lingkungan adalah institusi pesantren. Pesantren diyakini Kiai Sahal bisa melaksanakan peran ini mengingat posisinya yang menyatu dengan masyarakat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan mempunyai fungsi ganda. Pertama, sebagai lembaga pendidikan yang mampu mengembangkan pengetahuan, penalaran, keterampilan, kepribadian kelompok muda dan merupakan sumber referensi tata nilai Islami bagi masyarakat sekitar. Kedua, sebagai lembaga sosial di pedesaan yang dapat menggerakkan swadaya dan swakarsa masyarakat khususnya dalam melakukan perbaikan lingkungan.
Upaya pembinaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan proyek. Kedua pendekatan motivasi. Atau keduanya dilakukan secara sekaligus. Pendekatan motivasi ini bisa dilakukan melalui jalur pendidikan di pesantren. Pendekatan motivasi walaupun memerlukan waktu realtif panjang diyakini akan memberi dampak lebih positif karena kelompok sasaran secara berangsur akan mau menguibah sikap dan prilakunya secara persuasif. Perilaku dan sikap acuh tak acuh mereka kepada masalah lingkungan hidup akan berubah menjadi sikap dinamis terhadap pembinaan lingkungan hidup.
Keterlibatan pesantren dalam memberikan pengertian mengenai dampak lingkungan hidup bagi kehidupan manusia merupakan salah satu bentuk kontribusi dari unsur-unsur di luar pemerintah dalam pembinaan lingkungan hidup. Bila upaya-upaya pembinaan lingkungan hidup dilembagakan dalam wadah/organisasi maka akan memberi pengaruh lebih luas dibandingkan jika dikelola tanpa lembaga.
Upaya-upaya penanaman kesadaran bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan perlu menjadi gerakan social. Alasannya, pada saat ini dunia dihantui oleh krisis lingkungan hidup. Kualitas sumber daya alam yang tersedia di darat dan di laut sudah semakin merosot (degradasi). Menyadari hal itu maka sekarang sedang marak disosialisasikan model pembangunan berkelanjutan (sustainable development) atau pembangunan berwawasan lingkungan. Suatu pembangunan dianggap berkelanjutan jika kegiatannya selain memenuhi persyaratan ekonomi juga memenuhi persyaratan sosial budaya. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan senantiasa menghendaki peningkatan kualitas hidup manusia dan selalu berorientasi jangka panjang dengan prinsip-prinsip keberlanjutan hidup manusia sekarang dan akan datang.
Memperhatikan Lima Prinsip
Secara umum ada lima prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan. Pertama, keadilan antar generasi (intergenerational equity). Prinsip ini berangkat dari suatu gagasan bahwa generasi sekarang menguasai sumber daya alam yang terdapat di muka bumi sebagai titipan untuk dipergunakan generasi mendatang. Kedua, prinsip keadilan dalam satu generasi (intragenerational equity) merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan di antara sesama satu generasi termasuk dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau tidak terdapat kesenjangan antara individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat.
Ketiga, prinsip pencegahan dini (precautionary principle). Prinsip ini mengandung pengertian; tidak alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan apabila terdapat ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan. Keempat, prinsip perlindungan keanekaragaman hayati (biodiversity conservation). Keanekaragaman hayati perlu dilindungi karena memberikan dan menjadi sumber kesejahteraan bagi umat manusia. Kelima, perlunya internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif. Gagasan dari pinsip ini adalah biaya lingkungan dan sosial harus diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber daya alam. Sedangkan mekanisme insentif berupa program peringkat kinerja yang dimaksudkan untuk mengubah perilaku dan nilai-nilai di masyarakat melalui publikasi kinerja industri secara periodik.
Gerakan menjaga kelestarian lingkungan seperti yang dilakukan oleh BPPM Pesantren sangat mendesak dilakukan karena didasari sejumlah alasan. Pertama, bangsa kini sedang menuju ke arah krisis sumber daya alam. Diperkirakan, laju kerusakan hutan Indonesia saat ini telah mencapai 2,4 juta ha pertahun. Saat ini luasan hutan primer yang tersisa di berbagai pulau utama di Indonesia semakin memprihatinkan luasannya, berkisar antara 3,9% – 27,2 %. Hanya Papua yang masih menyisakan hutan primer sekitar 70% luas hutannya. Papua memiliki kondisi fisik yang berbeda dengan curah hujan dan perbedaan kelerengan yang ekstrim membuat kawasan ini sangat peka tanpa hutan sebagai penutup tanahnya. Luasan hutan primer ini menggambarkan luasan kawasan resapan air utama yang berada di tingkat pulau. Kawasan-kawasan tersisa ini sebagian besar ada di kawasan-kawasan lindung, yang juga menjadi gudang kekayaan keragaman hayati dunia. Di kawasan hutan lindung di Riau misalnya, keragaman hayati untuk tanaman mencapai 218 jenis per 200 meter persegi, Jambi (118), Kalimantan (110), dan Papua (90). Kawasan-kawasan seperti inilah yang akan diubah menjadi kawasan pertambangan.
Satu-satunya jenis hutan yang berada dalam kondisi baik adalah hutan lindung dan kawasan konservasi. Kurang dari 30% luasan Indonesia diperuntukkan bagi kawasan konservasi dan hutan lindung yang tersebar di pulau dan perairan Indonesia. Saat ini kawasan-kawasan tersebut mengalami tekanan sangat berat, mulai dari praktek illegal logging, kebakaran hutan serta tumpang tindihnya peruntukan antara hutan dan perkebunan kelapa sawit, HPH serta pertambangan. Ironisnya, penduduk lokal yang secara adat menguasai kawasan-kawasan tersebut, terus dikesampingkan dalam proses pengambilan keputusan dan perlindungan kawasan. Mereka bahkan diasingkan dari tanahnya sendiri. Jika kawasan-kawasan lindung juga dibuka untuk pertambangan maka laju kerusakan hutan akan semakin tinggi, begitu pula bencana lingkungan yang akan menyertainya.
Beberapa penyebab kerusakan hutan adalah maraknya praktek industri pertambangan yang kurang memperhatikan aspek keselamatan ekologis, eksploitasi kayu hutan dan kebakaran yang merusak areal hutan. Di lokasi-lokasi pertambangan terlihat jelas bagaimana wajah hutan Indonesia yang hancur karena penggalian, pembuangan limbah batuan (over burden) dan limbah tailing (sisa-sisa pertambangan) serta aktivitas penunjang operasi tambang lainnya. Beberapa perusahaan yang akan menghentikan kegiatan tambangnya menyatakan tidak mampu menghutankan kembali bekas-bekas lubang tambang dan kolam limbah mereka. Lubang-lubang itu dibiarkan terus menganga dan menjadi danau asam beracun pasca penambangan. Begitu pula kolam limbah tailing akan jadi hamparan pasir yang mengandung logam berat dalam kurun waktu sangat panjang.
Komitmen Kiai Sahal terhadap pentingnya pelaksanaan program pembangunan yang berwawasan lingkungan sedikit banyak telah ikut mewarnai sejumlah keputusan yang dilahirkan NU. Salah satu produk pemikiran NU yang memberikan apresiasi terhadap upaya menjaga keselamatan lingkungan dapat disimak dalam Hasil Keputusan Muktamar ke-30 pada tanggal 24 Nopember 1999 di Lirboyo Kediri. Sebagian isi hasil muktamar mengkritisi model pembangunan pemerintah yang selama ini dinilai telah mengabaikan faktor keseimbangan dan kelestarian alam.
Penerapan konsep dan teknologi revolusi hijau yang mengedepankan masukan sintetis, kimia dan teknologi tinggi serta pemaksaan paket-paket teknologi terapan yang semula dicita-citakan akan menghasilkan swasembada pangan pada tahun 1984 ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Yang terjadi justeru penurunan produksi, sehingga sejak tahun 1994 Indonesia kembali mengimpor bahan pangan secara besar-besaran. Di lain pihak, penerapan revolusi hijau dirasakan memberikan dampak negatif cukup serius terhadap lingkungan adalah yaitu berupa terganggunya kehidupan kesehatan petani oleh racun pestisida, tercemarnya air dan tanah oleh bahan kimia, rusaknya ekosistem oleh pestisida sehingga sering terjadi serangan hama, memadatnya lahan (tanah mati, tak ada kehidupan organisme di dalamnya) sehingga kemampuan produksi lahan dan keanekaragaman hayati turun serta hilangnya varitas lokal akibat adanya pemaksaan pemakaian varitas unggul.
Revolusi hijau juga dirasakan telah memberi dampak kurang baik di bidang sosial-ekonomi karena telah menjadikan petani bergantung pada input, informasi, teknologi eksternal, tersumbatnya kreativitas petani karena sistem komando (sitem penyuluhan-PPL), hilangnya pengetahuan dan teknologi petani (indigenous knowledge and technology), hilangnya hak petani mengelola lahannya sendiri dan menentukan harga jual hasilnya dan lenyapnya penghasilan petani akibat meningkatnya biaya produksi.
Stategi pertanian dengan relovolusi hijau juga dinilai gagal atau belum optimal dalam menciptakan kondisi masyarakat desa yang lepas dari kemiskinan. Kegagalan terjadi karena program itu kurang disertai dengan upaya reformasi di sektor lain. Sebagai contoh, pemerintah secara nasional dirasakan secara lamban dalam menata sistem pemilikan dan penguasaan tanah. Pemilikan dan penguasaan tanah masih didominasi oleh elit desa yang kondisi ekonomisnya lebih mapan. Merekalah yang lebih banyak memanfaatkan modal atau dana pinjaman dengan bunga rendah yang disediakan pemerintah. Mereka juga yang memanfaatkan benih, pupuk dan obat-obatan pertanian yang harganya telah disubsidi pemerintah sekaligus memanfaatkan lembaga-lembaga pembangunan pertanian seperti kelompok tani yang di dalamnya banyak hal dan informasi yang menyangkut teknologi dan perbaikan sistem pertanian.
Sementara, para petani marginal, petani gurem dan petani buruh tani menjadi tersisih dari fasilitas itu. Mereka tidak dapat memanfaatkan pinjaman bunga rendah karena tidak memiliki tanah agunan. Mereka juga tidak dapat menikmati subsidi benih, pupuk dan obat-obatan pertanian karena tidak berkepentingan. Mereka tidak memiliki akses pada lembaga-lembaga pembangunan pertanian karena dianggap bukan kelompok sasaran.
Kebijakan pembangunan pertanian yang tidak berpihak kepada rakyat (petani) dan lingkungan tersebut kemudian diperparah lagi oleh berbagai kebijakan seperti tentang alih fungsi lahan pertanian ke industri yang umumnya dilakukan secara paksa, monopoli distribusi hasil (BPPC, KUD dan BULOG), intervensi pemasaran barang/ produk yang menguntungkan pabrik kepada petani melalui paket KUT, keberpihakan pemerintah kepada pabrik gula, berlangsungnya kooptasi petani oleh organisasi yang mengatasnamakan petani (HKTI), pemaksaan konsep inti plasma dan lainnya. Berbagai kebijakan di atas telah menempatkan petani sebagai tumbal-tumbal pembangunan industri di negerinya sendiri dan sebagai makhluk yang tak berdaya, tersisih dan tak punya suara.