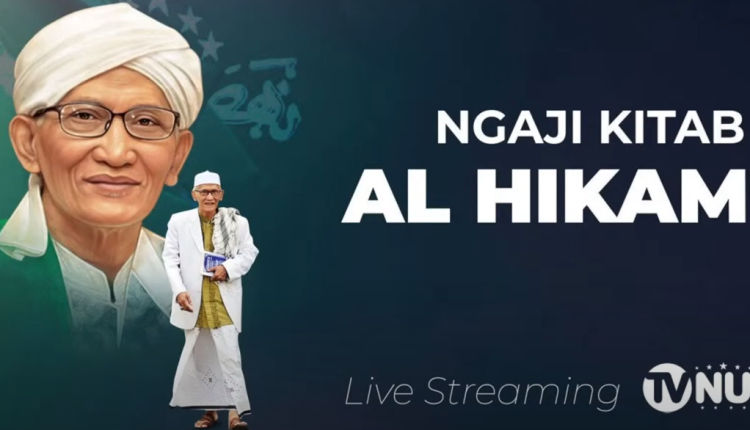Yahya bin Muadz berkata:
الورع أن لا تتَحرَّكَ ولا تسكن، على أن ترى الله في الحركة والسكون، فإذا رأيت الله ذهبت الحركة والسكون، وبقيت مع الله
“al-Wara’ an Lâ Tataharraka wa Lâ Taskuna. Alâ wa Tarâllâha fîl Harakah was Sukûn. Fa idzâ Ra’aitallâha Dzahabatil Harakatu wa al-Sukûnu, wa Baqîta Ma’allâhi”.
Artinya. Wara’ atau menjaga diri dari yang syubhat adalah bahwa engkau tidak bergerak dan tidak pula diam, kecuali engkau melihat Allah dalam gerak dan diam itu. Maka ketika engkau melihat Allah, lenyaplah gerak dan diam tersebut, yang tersisa hanyalah engkau dengan Allah s.w.t..
Sebagaimana dibahas pada kajian dan edisi sebelumnya, bahwa wara’ atau wira’i mempunyai makna ketakwaan tingkat tinggi yang ada pada diri seseorang. Dalam spektrum yang lebih luas, wara’ bermakna sikap seseorang yang tidak hanya menjauhi sesuatu yang haram, namun juga menjauhi sesuatu yang syubhat demi menjaga kesucian hati dan kedekatannya dengan Allah s.w.t..
Sikap Ihtiyât atau berhati-hati dalam menjalani lampah hidup agar terhindar dari perkara syubhat merupakan kondisi spiritual seseorang, di mana ia tidak melakukan aktivitas maupun berdiam diri, melainkan menyadari kehadiran Allah di dalamnya. Ketika seorang hamba mencapai maqam spiritual ini, yakni melihat Allah dalam segala hal, maka gerakan maupun keheningan tidak lagi menjadi pusat perhatian.
Namun yang tersisa hanyalah kesatuan hubungan spiritual antara dirinya dengan Allah s.w.t.. Gerakan yang didemonstrasikan oleh seorang hamba hanyalah wadah yang memuat apa yang terjadi di dalamnya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian kaum sufi: “Aku tidak pernah melihat sesuatupun kecuali aku melihat Allah di dalamnya”. Ketika spiritualitas seorang hamba sudah tertuju sepenuhnya kepada Allah, maka segala sesuatu selain-Nya seakan lenyap dari pandangan.
Menurut sebagian tokoh tasawuf, para ulama telah bersepakat bahwa halal sejati adalah sesuatu yang diperoleh secara langsung dari Allah, tanpa ketergantungan pada perantara duniawi. Kondisi seperti itu mencerminkan maqam tawakal, yaitu tingkatan tertinggi dalam menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah s.w.t.. Senada dengan itu, dikatakan bahwa: “Halal adalah sesuatu yang tidak membuatmu lalai dari Allah”.
Artinya, apapun yang diperoleh secara halal akan memperkuat hubungan seseorang dengan Allah, bukan malah menjauhkan sehingga melalaikan-Nya. Dalam harmonisasi syariat dan tasawuf, ada singkronisasi variabel di mana seorang hamba yang mengonsumsi makanan halal, cenderung akan selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.
Ketaatan itulah yang menjadi penghubung antara dirinya dengan Allah s.w.t., sehingga apapun yang diperbuat oleh yang bersangkuan, selalu cengderung kepada perbuatan yang diridhai oleh-Nya. Hal itu diperbuat hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman apa yang Dia perintahkan kepada para rasul-Nya. Maka Allah berfirman: (Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh) (QS. Al-Mu’minun: 23:51). Dan Allah juga berfirman: (Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami rizkikan kepada kalian} (QS. Al-Baqarah: 02:172).
Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang seseorang yang menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut, dan berdebu. Ia menengadahkan tangannya ke langit sambil berdoa: “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku,” padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dengan yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?” (HR. Muslim, 1015).
Di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, banyak sekali ditemukan mengenai rizki yang Allah s.w.t. anugerahkan kepada seluruh makhluk-Nya. di antara ayat-ayat tersebut seperti:“Tidak ada suatu hewan melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)”. (QS. Hud, 11:06).
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, Rasulullah s.a.w. berpesan kepadanya seraya bersabda: “Wahai Hakim, sesungguhnya harta benda ini kelihatan hijau dan manis, barang siapa mengambilnya dengan cara yang baik, maka ia akan diberkahi, dan barang siapa mengambilnya dengan berlebihan, maka ia tidak akan diberkahi, yaitu seperti orang yang makan dan tak pernah kenyang, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah”. (HR. Bukhari, 5960).
Dari kedua nash dari al-Qur’an maupun al-Sunnah di atas, dapat dipahami bahwa seluruh makhluk Allah, baik hewan, dan manusia semuanya memperoleh rizki. Namun, yang perlu digaris-bawahi di sini adalah bahwa mereka punya cara yang berbeda-beda dalam memperoleh) rizki tersebut. Setidaknya, ada empat cara yang ditempuh hamba-hamba Allah dalam mendapatkan rizkinya itu,
yakni (1) di antara mereka ada yang memperoleh rizki dengan kehinaan (dzillah), di antara mereka (2) ada yang mendapat rizkinya dengan perantara kerja kasar dan direndahkan (imtihân). Begitu juga (3) di antara mereka ada yang memperolehnya dengan penantian (intidzâr), dan yang terakhir (4) di antara mereka juga ada yang memperoleh rizkinya dengan kemuliaan (al-‘Izz), yakni tanpa pekerjaan, tanpa penantian, dan tanpa kehinaan.
Adapun orang-orang yang memperoleh rizkinya dengan kehinaan adalah mereka yang meminta-minta. Maksudnya adalah mereka menyaksikan tangan-tangan makhluk, lalu merendahkan harga dirinya kepada mereka, meskipun dengan cara menjilat agar dikasihani dan diberi materi yang tak seberapa. Sedangkan mereka yang memperoleh rizkinya dengan kerja kasar adalah para pekerja dan pengrajin, yang mendapatkan rizki melalui pekerjaan dan usaha yang keras.
Adapun yang memperoleh rizkinya dengan penantian adalah para pedagang yang menunggu barang dagangannya laku, sehingga ia dapat membeli kebutuhannya dengan keuntungan yang diperoleh. Tidak sedikit ia tersiksa secara batin karena penantiannya itu, karena harus menunggu tanpa mengetahui apakah dagangannya akan laku atau tidak. Adapun mereka yang memperoleh rizkinya dengan kemuliaan, tanpa kerja kasar, tanpa menanti, dan tanpa hina, maka mereka adalah para kaum sufi yang memahami hakikat. Mereka selalu hadir di hadapan Allah Sang Maha Perkasa, lalu mereka mengambil bagian rizki mereka langsung dari kekuasann-Nya dengan penuh kemuliaan.
Menanggapi hal tersebut, Sahl bin Abdullah berkata: “Tidak ada asbab bersama iman, karena asbab itu hanya ada dalam Islam”. Pernyataan ini mendapat respons dari Syaikh Abu Thalib: “Maksudnya, dalam hakikat iman tidak ada pandangan terhadap asbab duniawi atau ketergantungan padanya. Justru pandangan terhadap asbab dan berharap kepada makhluk itu hanya ditemukan pada maqam Islam atau tingkatan syariat luar”. Apabila ditarik ulur ke dalam uraian epistemologis mengenai iman, islam, dan ihsan sebagaimana tertuang dalam hadis Jibril, ketiganya merupakan tingkatan yang berbeda dalam perjalanan spiritual seorang hamba.
Islam adalah tingkatan lahiriah, yang mencakup pelaksanaan syariat seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Pada maqam ini, seorang hamba masih terikat pada sebab-akibat duniawi (asbâb). Misalnya, seorang muslim yang berniaga karena ingin memperoleh rizki, ia menggantungkan hasil usahanya itu pada mekanisme sebab-akibat, seperti usaha, modal, strategi pasar, dan sebagainya. Ketergantungan kepada asbâb ini dalam ajaran agama diperkenankan bahkan diperintahkan, karena dalam konteks syariat, ia merupakan bagian dari etika terhadap sunnatullah.
Sebaliknya dalam hierarki iman sebagai bagian dari kerangka tasawuf, seorang hamba tidak lagi menyandarkan hati kepada asbab duniawi. Ia meyakini bahwa sebab hanyalah wadah lahiriah, sedangkan hakikat pengatur segala sesuatu adalah Allah s.w.t. semata. Karena itulah, maka Syaikh Abu Thalib mengomentari pandangan Sahl bin Abdullah di atas dengan penegasan bahwa dalam hakikat iman tidak ada “ru’yat al-asbâb” atau pandangan terhadap sebab, serta juga tidak ada “al-Sukûn Ilaihâ” atau ketergantungan hati kepada asbâb.
Karena, asbâb hanya boleh ada secara lahiriah, tetapi hati tidak boleh terpaut padanya. Artinya, bagi Syaikh Abu Thalib, kecenderungan bergantung secara hakiki hanyalah kepada Allah, sedangkan asbâb hanyalah perantara dalam dimensi lahiriah. Dalam epistemologi tasawuf, menggantungkan sesuatu hanya kepada Allah s.w.t. semata tanpa menafikan peran asbâb sebagai bagian dari sunnatullah disebut sebagai tawakkul hakiki. Wallâhu A’lam bis Shawâb.
(Transkip Pengajian Syarah al Hikam oleh Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar Pertemuan Ke-90 live di TVNU).